Jendela Seni,kali ini akan berbagi mengenai salah satu cerita rakyat di suku bugis yang kemudian disertai dengan upacara adat yaitu cerita tentang Meong Palo Karellae,meong palo karellae adalah salah satu episode dari epos La Galigo, suatu karya sastra yang
bersifat mitologis, tetapi pada hakekatnya nilai-nilai yang terkandung
di dalamnya adalah sesuatu positif dan universal.
Meong Palo Karellae (MPK) yang artinya kucing loreng ke merah-merahan (
Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang), di Luwu biasa disebut Meong
Palo Bolonge (MPB) yang artinya kucing loreng kehitam-hitaman, secara
prinsipil versinya tidak berbeda hanya menyangkut istilah dan cara
pandang seseorang terhadap Meong Paloe, apabila kucing tersebut dilihat
dari depan maka warna yang dominan adalah hitam keloreng-lorengan,
sebaliknya apabila dipandang dari samping maka kucing itu kelihatan
berwarna merah keloreng-lorengan. Sehingga sampai saat ini di kalangan
masyarakat Bugis bahwa kucing yang mempunyai warna merah atau hitam
keloreng-lorengan dianggap mempunyai aspek kedewataan, karena itu ia
harus diperlakukan sebagai makhluk yang sakral dan keramat.
Ada beberapa upacara yang mengiringi pembacaan teks (Meong Palo Karellae), antara lain :
1) Upacara Mappalili,
2) Upacara Maddoja Bine
3) Upacara Mappaddendang.
Upacara Mappalili : adalah upacara membangun Arajang (Alat-alat
kerajaan yang dianggap keramat dan sakral) menjelang musim panen, dalam
upacara ini setelah usai membacakan doa, Bissu biasanya menunjukkan
kesaktiannya dengan berkali-kali menusukkan senjata tajam ketubuhnya
tanpa terluka (Maggiri), dengan diiringi tabuhan gendang dan musik
tradisional Bugis yang seperti menghadirkan suasana magis. Apa yang
diperagakan para Bissu dalam tarian Mabbissu itu, berupa kekebalan
tubuh terhadap senjata tajam, sebetulnya manifestasi dua kekuatan yang
menyatu dalam diri Bissu : Kekuatan kelembutan, dan kekuatan
keperkasaan (Jalal dan Jamal) (Kombie,A.S,2003:200-201).
Bissu adalah sekelompok pendeta agama Bugis kuno pra-Islam. Ketuanya
digelari Puang Matowa atau Puang Towa. Bissu dalam naskah I La Galigo
adalah perantara antara manusia dan dewata sekaligus sebagai penasehat
para raja dan keluarganya dan menjaga Arajang (benda-benda pusaka
kerajaan). Mulan turunnya Bissu dipercaya sebagai pendamping Batara
Guru ketika turun ke bumi (dunia tengah).
Bissu secara fisik adalah campuran antara lelaki dan perempuan yang
secara filosofis dimaknai sebagai penggabungan kekuatan dan kelembutan.
Sampai saat ini Bissu masih berperan banyak dalam ritual-ritual Bugis,
salah satunya upacara Mappalili (Halilintar Latief dalam
Kombie,A.S,2003:199-200).
Maddoja Bine : diadakan sesudah 20 malam usianya upacara Mappalili,
diadakan lima hari lima malam. Tiap malam teks MPK dibacakan oleh
seorang Bissu atau orang-orang tua yang dijadikan sesepuh di hadapan
seonggokan bibit padi yang akan ditanam di tengah-tengah rumah.
Mappaddendang : Diadakan sesudah panen, sebagai tanda kesyukuran atas
berhasilnya padi. Upacara ini biasanya diadakan di muka istana kerajaan
dengan mempertunjukkan berbagai macam kesenian, sambil menyaksikan
para Bissu mempertunjukkan tarian-tarian ritual yang kadang disertai
dengan atraksi yang cukup mendebarkan (Maggiri).
Saat ini upacara tersebut sudah jarang dilakukan kecuali di Kecamatan
Segeri Kabupaten Pangkep, dan di Kabupaten Barru, Kemudian dilestarikan
kembali di Kabupaten Bone. MPK (Meong Palo Karellae) mengandung aspek
sosial budaya masyarakat Bugis.
Berikut Adalah Ringkasan Cerita Dari Meong Palo Karellae:
Sebuah mitos mengenai We Oddangriu puteri Batara Guru yang setelah
meninggalnya, menjelma menjadi Dewi Padi (Sangiangserri), Meong Palo
Karellae adalah penjelmaan dari ibu susuan (Inannyumparenna) We
Oddangriu menceriterakan pengembaraan Sangiangserri dan pengikutnya ke
beberapa negeri Bugis untuk mencari manusia yang berbudi baik dan
berlaku sopan santun.
Batara Guru adalah anak lelaki tertua dari mahadewa langit To Palanroe
(sang pencipta), juga dinamai To Patotoe (sang pengatur takdir
manusia), dari Datu Palinge (wanita sang pencipta) turun ke bumi atas
keinginan dari semua Raja laki-laki dan Raja perempuan di langit dan
dibawah bumi, sesudah para keluarga besar mahadewa di langit mengadakan
rapat, maka diputuskan untuk mengirim Batara Guru guna menciptakan
tulang bumi, yang ketika itu masih kacau balau sebagai tempat yang
dapat didiami oleh manusia.
Oleh karena Batara Guru tidak dapat tinggal dibumi, selanjutnya
ditentukan bahwa kakak lelaki kembar ibunya, mahadewa dari dunia bawah
yang bernama Guru ri Sa’lang, dan istrinya dari saudari kembar Patotoe
yang bernama Sinau Toja (yang dinaungi oleh air), anak perempuan mereka
Wenyili Timo Tompoe (To Ompoe’) ribusa empong (yaitu yang muncul dari
buih gelombang) akan dikirim ke bumi, disamping kelima puteri-puterinya
lainnya dari bawah bumi untuk dikawinkan dengan Batara Guru sebagai
istri pertama dan utama.
Batara Guru sesudah itu turun ke bumi melalui pelangi di dalam batang
bambu dengan pengiringnya. Sedang Wenyili Timo dengan rombongannya
muncul dari buih-buih ombak laut, dan disambut dengan tangan terbuka
oleh Batara Guru. Tempat pertemuan ini adalah Luwu yang pada waktu itu
dinamai Wara’. Dari sinilah peradaban menyebar selanjutnya keseluruh
Sulawesi, dan bahkan keluar negeri, (Morris,2007:5-7).
Pada suatu waktu Batara Guru termenung dan melepaskan pandangan ke arah
matahari terbit. Tiba-tiba dilihatnya di sebelah timur datang sebuah
sinar menerangi lautan, laksana bara api memercik-mercik berkilau-kilau
di permukaan laut terhampar. Berkatalah Manurunnge (Batara Guru)
kepada dayang-dayangnya : ” Apakah itu (hai) We Senriu, (hai) We
Lele-Ellung, (hai) Apputalaga, bagaikan api menyala-nyala di atas
samudera itu?” Baru saja lepas pertanyaan Manurunnge itu, tiba-tiba
muncullah We Nyili’Timo di atas air (Busa empong), di elu-elukan oleh
cahaya cemerlang laut terhampar. Dengan penuh rasa gembira, Manurunnge
pun melihat kedatangan sepupunya, teroleng-oleng di atas lautan, maka
bersabdalah Batara Guru “Berangkatlah engkau semua putera-putera
dewata, menerangi, menyonsong kedatangan Datu junjunganmu!” Maka
sekalian anak Datu sama melompat berenang, menyonsong Datu
junjungannya. Seolah-olah madu tergenang dalam hati Batara Guru
memandang sepupunya, menyuruh angkat naik ke pantai, dan mengundang
masuk istana. Pada saat itu, lupalah Batara Guru kehidupan di
Botillangi (dunia atas) setelah bergaul dengan sepupunya sebagai
suami-isteri. Mereka senantiasa duduk bersanding, menikmati kipasan
angin dari kipas emas kemilau. Sesudah tiga bulan lamanya, We
Nyili’timo berdiam diatas bumi, ia pun mengidamlah. Tak enak
perasaannya, tidak ada barang sesuatu yang dapat diterima oleh perutnya.
Pada suatu hari yang cerah, kedua suami-isteri melepaskan pandangan
melewati jendela istana. Wenyili’timo pun memandang burung-burung
beterbangan. Di antaranya burung-burung itu terlihat seekor yang
menerbangkan buah nangka di paruhnya, ada yang menerbangkan pepaya masak
dan pisang. We Nyili’timo’ pun menyeru, “memanggil burung-burung itu
dan berkata :”Bawaan burung-burung itu tak akan memabokkan, karenanya
ingin saya memakannya”.
Tepat ketika matahari bersemayam di tengah-tengah langit, bayang-bayang
tak condong ke barat ataupun ke timur, maka diulurkanlah turun Puang
ri Lae-lae yang tinggal dilereng gunung Latimojong, diulur juga I We
Ampang Langi’, yang akan menjadi dukun beranak di istana. Sesudah tujuh
bulan kandungan We Nyili’timo’, bersalinlah ia seorang puteri,
diberinya nama We Oddang-Riu’. Tetapi tujuh hari saja usia puteri itu,
terseranglah ia penyakit perut yang menyebabkan kematiannya. Maka
dicarinya hutan untuk tempat menyimpannya, tempat yang akan dijadikan
kuburannya. Setelah tiga malam meninggalnya We Oddangriu’, datanglah
kerinduan dalam hati Manurunnge kepada almarhumah puterinya. Ia pun
keluar menuju kuburan puteri tercinta. Tetapi apa yang dijumpainya
hanyalah padi menguning. Itulah sangiangserri. Ada yang putih, ada yang
hitam, ada yang merah memenuhi padang, meliputi daratan, memenuhi
parit-parit. Maka dibawanya sangiangserri itu pulang ke istananya.
Maka berkatalah To PalanroE (Lapatotoe) di Botillangi’ kepada puteranya
:” Hai anakku itulah puterimu yang menjelma menjadi sangiangserri”.
Tetapi janganlah engkau memakannya dulu. Nantilah setelah lewat
beberapa tahun, setelah engkau telah melupakannya, barulah engkau
memakannya. Sebelumnya makanlah jagung”. (Mattulada;1985:395-396).
Tatkala Sangiangserri (Dewi Padi) merasa tidak lagi dihargai oleh
orang-orang Luwu, ia tidak lagi di tempatkan pada singgasananya,
penduduk tidak lagi mematuhi petuah, pantangan, dan
larangan-larangannya, ia dimakan tikus pada malam hari, di totok ayam
pada siang hari, karena hanya Meong Palo Karellae yang mengawalnya
justru ia disiksa oleh manusia, maka iapun sepakat dengan MPK dan
pengawal-pengawalnya untuk pergi mengembara (Sompe).
Dalam pengembaraan itu, mula-mula sangiangserri dan rombongan tiba di
Enrekang, lalu terdampar di Maiwa (Duri), kemudian berturut-turut ke
Soppeng, Langkemme, terus ke Kessi, Watu, Lisu, sampai akhirnya tiba di
Barru. Perjalanan dari Enrekang sampai ke Lisu, penuh dengan berbagai
dengan derita dan tantangan, sikap dan perlakuan orang-orang yang tidak
senonoh, kucing (MPK) disiksanya habis-habisan, ia dan rombongan
kelaparan, kehausan, belum lagi kepanasan yang menimpanya pada siang
hari, dan kedinginan pada malam hari.
Tetapi ketika ia di Barru, ia menemukan sesuatu yang lain dari
tempat-tempat yang telah dilaluinya. Sangiangserri (Sanghyangsri) dan
rombongan di sambut dengan penuh kehangatan, dijamu, diistirahatkan di
Rakkeyang (loteng), ditambah dengan sifat keramah-tamahan penduduk,
keadilan dan kebijaksanaan penguasa, membuat Sangiangserri dan
rombongan betah.
Sayang sekali Sangiangserri sudah terlalu letih, lelah, dan sedih
mengingat suka duka perjalanannya, dan sifat-sifat anak manusia yang
ditemuinya, sehingga ia bertekad untuk meninggalkan bumi, untuk
kemudian kembali ke langit menemui kedua orang tuanya yang bertahta di
Boting Langi (Kerajaan Langit).
Tetapi sesampainya di langit, Sangiangserri beserta rombongan tidak
diperkenangkan oleh kedua orang tuanya untuk menetap dilangit, sebab
memang nasib dan kejadiaannya telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk
memberi kehidupan kepada orang-orang bumi (Peritiwi). Karena itulah
akhirnya mereka terpaksa kembali ke bumi, dan Barru lah yang dituju
sebagai tempat menetap mereka.
Tujuh hari tujuh malam sesudah Sangiangserri tiba di Barru, barulah ia
memberikan petunjuk-petunjuk, petuah-petuah, nasehat-nasehat, serta
pantangan-pantangan, khususnya yang berhubungan dengan pertanian, dan
norma-norma masyarakat Bugis, baik menyangkut lapangan hidup pertanian,
maupun sikap dan perilaku yang patut (Sitinaja) dimiliki oleh
masyarakat, agar masyarakat tetap makmur, tenteram, dan sejahtera.
Hal ini dimungkinkan karena dengan demikian Sangiangserri akan menetap
di Barru, dan itu pertanda sebagai kemakmuran dan kesejahteraan. (dapat
dibuktikan bahwa Arung Barru (Raja Barru) adalah keturunan Raja Bone,
Mappajunge ri Luwu dan Sombae ri Gowa).
Inilah yang menceriterakan kucing loreng kehitam-hitaman atau kucing
loreng kemerah-merahan, juga disebut Cokie, Meong Paloe dan Posa’e.
Dia (MPK) berkata :” Ketika aku bermukim di Tempe, menetapku di Wage,
meski belanak saya makan, meski bete kubawa berlari, tak pernah aku di
usik, sabar dan pemurah, tuanku yang punya rumah.
Kemudian aku dihina Punna Langi (Penguasa Langit), tak di senangi oleh
Dewata, diatas di Ruangllette, dibawah di Peretiwi (Dunia Bawah). Aku
lalu terbuang di Enrekang, terdampar di Maiwa, tak teratur makananku.
Ketika tuan rumah pulang dari pasar, ia membawa ikan ceppe (semacam
ikan mujair), aku mendekat dan merampas, dekat yang paling besar.
Dipukulku dengan punggung parang, oleh yang empunya ikan ceppe,
bagaikan pecah kepalaku, seperti keluar biji mataku,
berkunang-kunanglah penglihatanku, bagaikan keluar isi otakku, melayang
semangatku, tersingkap jiwa ragaku, padam pelita di dalam, perasaan
hatiku, pupuslah sudah kekuatanku, bergetar-getar (Seluruh) tubuhku.
Sembari berlari mendengus, dibawah dapur, bagaikan pupus di dalam,
perasaan hatiku, berdenyut-denyut sudah, seluruh anggota tubuhku, maka
tersalah semuanya, urat-urat kecilku, bergetar-getar pula seluruhnya,
semua urat-urat besarku.
Kemudian kembali dilemparnya aku dengan sakkaleng, oleh tuanku yang
punya rumah. Akupun berlari diatas papan dapur, ia pun melempar lagi
aku dengan pabberung, oleh tuanku yang memasak. Kulari mendengus, di
bawah dapur, ditusuknya aku dengan puntung kayu bakar, oleh tuanku yang
memasak, kemudian dilanjutkan dengan menusukku dengan pabberung, aku
pun lalu terjatuh ke tanah.
Kemudian aku di patiti (memanggil anjing dengan menggonggong), tuanku yang punya rumah, maka gegerlah semua orang.
Pada berdatangan orang yang menumbuk padi mengusirku dengan alu,
memukulkan dengan alat pemukulnya, melemparkan nyirunya (Pattapi),
berserakanlah padinya, tertumpah berasnya, menumpuk sambil
tersungut-sungut, berhamburanlah sebelah menyebelah, tanpa ia tunduk
memungutnya. Ayam pun kemudian membawa lari, sebutir setangkai. Tak
henti-hentinya mengomel, tuanku yang menumbuk, ada juga yang mengusirku
dengan siak (mengusir kucing dengan kata sih) gegerlah lagi semua
orang, perempuan laki-laki, akupun berlari memanjat, pada tiang yang
sampai rumah, terus-terus aku naik, hingga sampai di rumah.
Kemudian aku masuk di bawah tenun, ditusuknya aku dengan alat tenun,
oleh tuanku yang bertenun. Akupun berlari terengah-engah, di bagian
rakkeyang, tak henti-hentinya memburu, tuanku yang punya ikan ceppe.
Langsung aku naik, di rakkeyang, disusulnya aku yang punya rumah. Lalu
aku berlari berlindung, dibawah usoreng (tempat tumpukan padi di
rakkeyang), menyelundupkan kepalakaku, mengunci diriku, dibawahnya We
Tune (nama lain dari Datu Sangiangserri), ratunya sangiangserri tak
henti-hentinya marah, isteri yang empunya rumah, laksana kabut yang
mengepul, raut mukanya dipandang, tak henti-hentinya mengumpat,
laki-laki perempuan, seluruh isi rumah.
Kebetulan sekali, nyenyak tidurnya, Datu Sangiangserri , ia diserempet
oleh ujung cambuk, ia pun berpaling terkejut, bangkit dengan
awut-awutan, Datu Sangiangserri. Alangkah ibanya jiwanya, pilu
perasaannya, melayang semangatnya, sedih di dalam, perasaan hatinya,
Datu Sangiangserri.
Sembari menangis We Tune’ berkata : sang keturunan pajung (gelar
bangsawan tertinggi di Luwu) :” Bangunlah sekalian ! padi ketan padi
biasa, semua padi yang setia, tak usah tinggal menderita, di tempat
usoreng ini. Bangkitlah kita pergi mencari sifat-sifat yang baik, aku
tak mau lagi tinggal disini, di totok oleh ayam, dimakan oleh tikus,
sebab hanya kucing yang diharapkan untuk menjaga kita, berjaga-jaga
tanpa tidur, malam dan siang, menangkap tikus, agar tidak gugur
tangkaiku, maupun pengikatku, justru dialah (MPK), yang sangat dibenci,
oleh isi rumah”. Belum lagi habis pembicaraan, Datu Sangiangserri,
maka pada bangkitlah, seluruh isi rakkeyang, sama duduk melingkar
mengelilingi tumpukan padi, besar kecil, beras ketan beras biasa, semua
padi yang banyak, semua padi yang setia. Belum lagi hancur daun
sirihnya, belum sempat berkedip mata, maka sama bergerak, semua padi
yang banyak, diarak bergerak, di muka We Tune, Datu Sangiangserri.
Berkata sembari menangis We Tune :” Bagaimana tanggapanmu, menurut
pikiranmu, perihal dibencinya sang kucing, disiksa siang malam. Sebab
menurut pendapatku, di dalam sanubariku. Lebih baik kita pergi membuang
diri di kampung yang jauh, mencari budi pekerti yang baik. Siapa tahu
kita mendapatkan orang sabar dan berpasrah diri, sesuai keinginan kita,
tahu menghargai Wisesa (Sangiangserri), menaikkan padi, tidak cemburu
hati terhadap tetangganya, sabar berpasrah diri, terhadap sesama
manusia, laki-laki yang jujur (lempu), wanita yang dermawan (malabo),
mengantar orang yang bepergian (marola), menjemput orang yang datang
(madduppa), memberikan makan orang yang lapar, memberi minum orang yang
haus, menyarungi (memberi sarung) kepada orang yang telanjang,
menerima orang yang susah, menampung orang yang terdampar, menerima
orang yang dibenci, menerima semua orang, yang diperlakukan
sewenang-wenang, oleh sesama manusia” inilah dinamakan malabo
(dermawan).
Serentak sama mengiya, semua padi yang banyak, juga gandum dan jagung, serta semua teman-temannya.
Belum lagi hancur daun sirih, belum sempat mata berkedip, maka sama
berangkatlah, semua padi yang banyak, mengikuti ia turun, di arak dengan
tenang, Datu Sangiangserri.
Kemudia ia sampai berdesakan, dirumah Matoa, Sulewatang Maiwa, yang
diikuti menurun, oleh Datu Meong Paloe, memenuhi sebagian rumah. Belum
lagi hilang letihnya, duduknya dirumah, Datu Sangiangserri, kebetulan
sekali, sedang makan orang dirumah, menyendok nasinya secara
berhamburan, menyuap tanpa memasukkan di mulut sehingga nasi
berhamburan di lantai, tanpa tunduk memungut, ibu yang melahirkannya,
dan tidak mau di tegur, terhadap teman-temannya.
Kemudian ia (penghuni rumah) berpaling berontak, menangis
meronta-ronta, merajuk tak henti-hentinya, sembari menggaruk-garuk
kepalanya, dan menarik rambutnya, diiringi dengan keringat yang
bercucuran. Melemparkan nasinya, berhamburanlah ia, ke kanan dan ke
kiri. Marah nian bapaknya, juga ibu yang melahirkannya, di
sumpah-sumpahinya anaknya, juga teman-temannya, dan berkelahi dengan
suaminya.
Kemudian ia berpaling sembari berkata, Datu Sangiangserri, terhadap
teman-temannya :”Saya tak ingin bermalam, tidak ditakdirkan We Tune,
Tuhan Pabare-baree, di atas di Boting Langi, di bawah di Peretiwi,
duduk bertahta di Maiwa, memberi kehidupan orang bumi. Tak kusenangi
perbuatannya, juga sifat-sifatnya, matoa petani tersebut, Sulewatannya
Maiwa. Turutlah kalian! Kita pergi, mencari sifat-sifat yang terpuji,
agar kita menemukan, sesuai kehendak hati kita perempuan yang rapih,
lelaki yang berpasrah diri, lapang dada di dalam sanubarinya (baik
hati), tidak culas, berpasrah diri terhadap sesama manusia, tahu
menjemput wisesa (padi), menaikkan Sangiangserri di rakkeyang.
Serentak mereka berangkat, semua padi yang banyak mengikuti menurun,
Datu Sangiangserri, dipikul oleh air, bertelekan tanah, menyeimbangkan
(badan) pada angin, berjalan beriring-iringan, Datu Sangiangserri.
Belum hancur daun sirih, belum lagi mata berkedip, maka ia pun telah
membelakangi Maiwa, dan didepannya adalah Soppeng, di pinggirnya
terdapat Pattojo, dekat pula La Injong, yang mengarah ke Bakke.
Keesokan harinya, ketika langit cerah, matahari bersinar di balik
pegunungan, matahari yang bersinar. Fajar pun telah menyinsing, maka
berpalinglah berkata, Datu Sangiangserri, kepada teman-temannya :
“Sebaiknya yang mana kita harus tuju, apakah yang disebelah utara,
jalan yang menuju Bakke, ataukah yang disebelah barat, jalan yang
menuju Tanete”, maka serentak mengiya, semua teman-temannya dan
berkata:”Anginlah engkau dan aku hanya daun kering (Angikko ku
raukkaju), kemana tuan bertiup, ke situlah hamba terbawa”.
Kemudian singgah beristirahat sejenak, Datu Sangiangserri di
perantaraan kampung, menyebarkan baunya, harumnya menusuk hidung, di
dapatinya, Datu Tiuseng (bibit), gandum dan jagung, dan jelai yang
banyak, dalam keadaan sedih pada bertangis-tangisan, di luar kampung,
pada bersiap-siap untuk membuang diri.
Buntulah perasaannya, Datu Sangiangserri, karena tidak ditemuinya satu
pun, kampung yang bakal ditempatinya. Kemudian ia berpaling dan berkata
Datu Tiuseng, terhadap teman-temannya :”Perbaiki gerangan dirimu,
seperti aku melihat, tuan kita yang disembah, yaitu Tuan kita We Tune
Datu Sangiangserri, mari kita ikuti dari pada tinggal berdesakan, di
perantaraan kampung, dimakan tikus, di totok ayam, dan dimakan hama.
Belum lagi habis ucapannya, Datu Tiuseng, maka tibalah ia berdesakan,
keturunan mappajung, keturunan dari Boting Langi, keturunan dari
Peritiwi. Kemudian berpaling dan berkata, Datu Sangiangserri :
Dengarkan baik-baik kataku, Datu Barelle (jagung), Datu Tiuseng (bibit),
dan semua jelai yang banyak, aku bertanya baik-baik, apa gerangan yang
menyebabkan engkau duduk disitu, di luar perkampungan, serentak mereka
sujud sembari berkata, Datu Barelle, Datu Batae, Datu Riusenge, dan
semua jelai yang banyak :” Sudah terlalu sakit aku Tuanku, tidak dibawa
ke rumah, orang di Langkemme. Bawa aku Tuan, dan kita memilih tempat
menetap, kampung yang kau tetapkan”. Ia pun berkata, Datu Sangiangserri
:”Kendatipun demikian ucapanmu, biarlah singgah sejenak, di kampung
Langkemme, menenangkan perasaan. Siapa tahu kita menemukan, sesuai kata
hati kita, sabar dan berpasrah diri, lelaki yang jujur, perempuan yang
apik, dan berlapang dada, terhadap sesama manusia, tidak berbuat culas,
tidak cemburu hati, terhadap tetangganya, sabar dan pasrah, terhadap
anak cucunya, sabar dan tekun, tidak cemburu hati, terhadap orang-orang
sekampungnya”.
Ia pun menangis dan berkata, Datu Sangiangseri, terhadap teman-temannya
:”Tidak jadilah saya menetap, di Kampung Langkemme, saya sangat pedih
(melihat), marah tak tentunya, berkata-kata seenaknya, Matoa petani,
yang berkuasa di Langkemme, di sumpah-sumpahinya anaknya, disinggung
perasaan teman-temannya, disakitinya sekampungnya, orang yang cemburu
hati, terhadap tetangganya. Mereka mengundang bala yang dahsyat, oleh
sifat yang tidak terpuji”.
Ia pun mengulang lagi perkataannya, Datu Sangiangserri : ” Mari kita
berangkat, mencari sifat-sifat yang terpuji, siapa tahu kita menemukan,
sesuai kata hati kita. Sabar penuh pasrah, terhadap sesama manusia,
laki-laki yang pemurah, perempuan yang apik, berpasrah diri, terhadap
sesama manusia, diberinya kuru’ sumange’, keluarga dan sekampungnya,
tidak culas, tahu menjemput wisesa (padi), menaikkan ke rumah
Sangiangserri. Serentak mereka sama berangkat, turun kembali, Datunna
Sangiangserri, diusung oleh air, bertelekan pada tanah, menyeimbangkan
tubuh pada angin, melewati perantaraan kampung, ketika mentari di
rembang senja, bertemulah dengan gelap, pelita sang Datu pun telah
menyala, ketika ia telah membelakangi Langkemme.
Belum lagi habis daun sirih, belum lagi mata berkedip ia pun telah
berada di Ambang (kampung) Kessi, ia pun berpaling sambil berkata, Datu
Sangiangserri : “Marilah kita singgah sejenak, di kampungnya orang
Kessi, siapa tahu kita menemukan, sesuatu kata hati kita, itulah
kemudian yang kita tempati, menetap di dalam, tenggorokan manusia”.
Merekapun serentak mengiya, semua padi yang banyak, gandum dan jagung,
dan semua jelai yang banyak. Belum lagi habis daun sirih, belum lagi
berkedip mata, merekapun telah sampai di Kessi, langsung mereka naik,
di istana kerajaannya, Matoa petani, yang menguasai Kessi, memenuhi
sebagian rumah, mereka duduk, sembari bersandar dengan santai, pada
bagian tiang rumah.
Kebetulan sekali, sedang berkelahi dengan suaminya, orang di dalam
rumah. Dan ketika senja hari, mereka berlomba-lomba memasak, pada
menaikkan pancinya, menjejerkan belanganya, sembari duduk
berdesak-desakan di muka dapur. Ada yang sedang memegang sajinya, ada
yang mengayu akan sendoknya, sementara yang lain mengaduk peniupnya. Di
tengah-tengah dapur, dan memperebutkan puntung kayu bakar. Maka
menangislah sambil berkata, Datu Sangiangserri :”Dengarkanlah sekalian,
semua padi yang banyak, di Kampung Lakessi.
Tak kusukai perbuatannya, tak kusenangi sifatnya, wanita tercintanya,
Matoa petani, yang berkuasa di Lakessi. Mari kita turun ! pergi mencari
sifat yang baik, agar kita menemukan, sesuai dengan bicara (kata hati)
kita, sesuai dengan jalan pikiran kita, bicara yang tidak
bertentangan, wanita yang apik, laki-laki yang patuh, terhadap sesama
manusia, tahu menjemput wisesa, menaikkan Sangiangserri, tidak cemburu
hati, terhadap tetangganya, dan menerima orang yang kesusahan”.
Serentak mereka turun, diusung oleh air, bertelekan pada tanah,
menyeimbangkan tubuh pada angin, dan akhirnya beristirahat sejenak di
perantaraan kampung, sebab sudah terlalu lelah, Datu Sangiangserri,
berjalan jauh. Mereka kemudian naik di rumah sebelah timur, tak
mendengar suara apapun, dan tak melihat seorangpun, duduk menghidupkan
pelita ketika gelap mulai menjelang. Mereka tidur bersilang-silangan,
laki-laki perempuan. Serentak dia naik, Datu Sangiangserri, langsung
meraba, tempayan yang didudukkan, tak ditemuinya setitik airpun,
apalagi yang namanya seteguk, ke Datu Tiuseng, gandum dan jagung,
semuanya jelai yang banyak, Datu Meong Paloe. Kemudian mereka berkata
:”Kur jiwa semangatmu (Kuru’ sumange’mu), keturunan La Patotoe,
keturunan Datu Mangkau’, anginlah engkau ku daun kayu yang kering, di
atas engkau bertiup, datu engkau terdampar, kuikuti terbawa,
terbawa-bawa sampai, di dunia pammasareng (alam arwah).
Belum lagi lepas ucapannya, serentak mereka telah tiba berdesakan, di
rumah peristirahatannya, Matoa Watu, memenuhi rumah sebagian langsung
ia naik, Datu Meong Paloe, menghempaskan diri berbaring, diatas
onggokan padi, seketika ia langsung tertidur pulas. Belum lagi kering
keringatnya, Datu Sangiangserri, ketika lewat tengah hari, isteri yang
empunya rumah, tanpa mencuci kaki, langsung naik ke rakkeyang,
mengambil padi seikat. Bertepatan ketika itu, berbaringnya sang kucing,
di puncak onggokan padi tersebut, mengumpulkan dengan baik, desahan
nafasnya, sebab sudah terlalu capek, berjalan sepanjang jalan, rasa
laparpun telah memuncak, lapar dan dahaga, perasaan jiwanya, Datu Meong
Paloe. Bergetar-getar seluruh tubuhnya, bergerak-gerak dagingnya,
berkunang-kunang sudah penglihatanya. Ia kemudian diusir, tapi sang
kucing tetap saja enggan bergeser, Datu Meong Paloe, spontan ia naik,
menyepaknya dengan ujung kaki, maka terlemparlah sang kucing, terdampar
persis di depannya, Datu Sangiangserri.
Ia pun bangkit awut-awutan, sembari berpaling dan terkejut, Datu
Sangiangserri. Ia pun berangkat dengan mengamuk isteri yang empunya
rumah, diangkatnya padinya, dengan marah dan berjalan turun, menuju ke
lesung, tanpa mengistirahatkan sebentar, di tengah rumah. Ia pun
menumbuk dengan mulut komat-kamit, berhamburan sebelah-menyebelah,
tanpa tunduk memungutnya, maka ayampun membawanya lari, sebutir dan
setangkai.
Ia pun menangis sembari berkata, Datu Sangiangserri, terhadap
teman-temannya : “Ayo kita turun dan berangkat, hatiku sangat pedih,
melihat perbuatan takabbur, dari yang empunya rumah.
Maka serentak mereka berangkat, Datu Sangiangserri, diarak dengan
tenang, diusung oleh air, bertelekan pada tanah, maka menipislah sudah,
seluruh isi rakkeyang, penguasa di Watu.
Kemudian ia pun menangis dan berkata, Datu Sangiangserri “Ayo kita
turun, menelusuri takdir kita, yang telah ditetapkan, To Pabbare-baree
(yang memelihara), mencari sifat-sifat yang terpuji, siapa tahu kita
menemukan, wanita yang apik, laki-laki yang sabar, berpasrah hati,
terhadap sesama manusia, tahu menjemput wisesa, menaikkan
Sangiangserri.
Merekapun telah sampai d Lisu, menangis dan berkata We Datu :”Ayo kita
singgah sejenak, di istana kerajaannya, Matoa petani “Serentak mereka
mengiya, semua padi yang banyak, semua teman-temannya. Bertepatan
ketika matahari di rembang senja, bertemunya gelap, ketika mereka tiba
berdesakan, memenuhi rumah sepotong, bagaikan angin ribut yang datang,
suaranya kedengaran, tanpa kelihatan wujudnya, berhamburan menusuk
hidung, harumnya We Tune, memabukkan harumnya. Bertepatan sekali,
sedang makan minum orang Lisu, berjaga menghadapi bibit padinya, begitu
sulit nasinya (makan), menggerutu, di dalam jiwanya, isteri petani,
sumpah serapahnya tak henti-henti, kata di dalam hatinya :”Apakah
berhasil kelak, ataukah tidak, padi yang kupersiapkan, sudah terlalu
banyak, belanjaku yang tak habis-habisnya, perbuatan yang tak karuan,
Matoa petani, yang berkuasa di Lisu ini. Dan disini semuanya berkumpul,
keluarga dan sekampungnya, begitu sulit nasinya, itulah yang membuat
aku malu, berjalan di saksikan oleh orang”.
Tak henti-hentinya ia bersumpah, isteri yang sama keturunannya, Matoa
Lisu, kebetulan sekali suaranya di dengar, oleh Datu Sangangserri,
ketika menyerakkan baunya, bau-baunya We Tune’, memabukkan baunya.
Sembah sujud sembari berkata, Matoa petani itu :”Maafkan aku oh marupe
ingatlah tuan, dan maafkanlah hambamu, lalu kemudian ia berpaling,
kepada isterinya yang lalai; “ingatlah marupe musuhlah nafsumu,
batasilah murkamu” Dapatkah engkau gerangan Datu watena, keturunang
Mappajung, yang menyerbakkan baunya, dan memabukkan harumnya,
kasihanilah aku We Raja, duduklah di sini marupe, di kampungmu di Lisu
memberi makan orang bumi, simpanlah di luar langit, dan di atas bara,
amarahnya hambamu”.
Ia pun menangis dan berkata, Datu Sangiangserri : “Baik sekali
ucapanmu, hai Matoa petani, aku akan tetap pergi, mencari orang yang
berbudi pekerti, orang lapang dada, dan mempunyai sifat-sifat yang
terpuji. Biarlah aku pergi membuang diri, agar aku menemukan, sesuai
dengan ucapan, di dalam jiwaku, wanita yang apik, laki-laki yang jujur,
sabar dan berpasrah diri, terhadap sesamanya manusia, tahu menjemput
wisesa. Kiranya di situlah menetap, semangat sanubariku, barulah aku
berhenti merantau. Sebab saya tidak senang, ittikad yang tidak baik,
isteri yang sama turunannya, Matoa petani itu, tidak mengenal siapa We
Tune’, yaitu keturunan Lapatotoe anaknya I Lasangiang yang menetap di
Boting Langi, di bawah di Peritiwi, keturunan manusia pertama, anak
mappajung, membawa kesusahan yang tiada taranya, dan kesedihan, sampai
akhirnya terdampar di kampungmu”.
Sembah sujud dan bersumpah, Matoa petani, yang memerintah di Lisu,
menengadahkan kedua tangannya, menyesali diri tak henti-hentinya,
terhadap orang-orang yang ada di dalam rumah, terhadap isterinya yang
lalai, isteri seketurunannya, wanita durhaka, tidak mengenal We Tune,
keturunan yang disembah. Bagaikan pupus di dalam, perasaan hatinya,
Matoa petani, penguasa di Lisu.
Tanpa berpaling lagi, Datu Sangiangserri, langsung berangkat, diarak
dengan tenang, diusung oleh air, bertelekan pada tanah, dan
menyeimbangkan badan pada angin, melewati perantaraan kampung.
Ia kemudian singgah mengamati, perantaraan kampung, mereka pun datang
berdesakan, dipinggir rumah, Sulewatang yang memerintah, sebagai
penguasa di Lisu. Kebetulan sekali orang sedang bertengkar, sekeluarga,
Ia pun mendengarkan yang disebelah timur, maka tak seorangpun yang di
dengarnya, berkata-kata yang baik, perempuan laki-laki, penduduk Lisu,
dan tidak mempunyai pendapat yang searah, sekampung dan sekeluarga,
dibencinya semuanya, dan cemburu hati, terhadap sesamanya kita turun
berangkat, menelusuri suratan takdir kita, yang telah digariskan, oleh
To parampuk-rampuk’e, menelusuri jalan yang benar, berjalan jauh, agar
kita menemukan, orang yang sesuai dengan kata hati kita, sabar dan
berpasrah diri, pengasih dan pemurah, merendah diri, terhadap
teman-temannya, sekeluarga dan sekampung, jujur dan hemat, sabar dan
rajin, dan diatasi oleh Batara, dipayungi Batara, dan diliputi oleh
Peritiwi, agar kita menemukan, sesuai dengan kata hati kita, dan kita
pilih sebagai tempat menetap, semangat sanubari kita, menyatukan cahaya
semangat kita”.
Serentak mereka mengiya, semua padi yang banyak, padi ketan padi biasa,
semua padi yang setia, Serentak ikut pula rombongan, gandum jagung,
semua jelai yang banyak, Datu Meong Paloe, berbondong-bondong
mengikuti. Datu Sangiangserri, diarak oleh awan, bertelekan pada tanah,
menyeimbangkan tubuh pada angin, menelusuri perantaraan kampung,
mengikuti jalan yang panjang, mengikuti anak sungai yang panjang.
Mereka tidak lagi mengamati, semua kampung yang banyak, kampung yang
luas. Tiga hari tiga malam, jalan sepanjang jalan, merekapun tiba pada
sebuah persimpangan jalan, keturunan mappajung, keturunan yang
disembah, buntulah pikirannya, semua padi yang banyak, Datu
Sangiangserri. Mereka kemudian serentak berkata : “Aku menengadahkan
tangan Tuanku aku ada kulit bawang We Tune’, tenggorokanku di dalam,
akan datang La Puang, jawablah kata sepotong, keturunannya yang
disembah, anak mappajung, kemana gerangan tibanya, matahari itu”.
Mereka kemudian menemukan simpang jalan, yang menuju ke Barru, mereka
lalu sembah sujud, semua padi yang banyak, “Kemana gerangan jalan yang
kita tuju, apakah kita melewati, jalan menuju Barru? “Menjawab dan
berkata, Datu Sangiangserri :” Sebaiknya kita lewat, jalan yang menuju
Barru, siapa tahu kita menemukan, sesuai dengan kata hati kita,
menampung orang yang terdampar, menerima orang kesusahan, sabar dan
pasrah, jujur dan berhati-hati, dilindungi aku Batara, diliputi oleh
Peritiwi, memusuhi nafsunya, dan membatasi marahnya.
Sebab menurut firasatku, di dalam sanubariku, di sinilah (Barru) tempat
menetapku, rumah mahligainya, Pabbicara di Barru, terang benderang
kulihat pelitanya, penuh semangat perasaanku, mendengar suara
kawalakie, rajin menegur, terhadap anak cucunya, diberinya kuru’
sumange’, terhadap semua teman-temannya.
Tempat yang kita pilih sebagai tempat menetap, adalah yang berlapang
dada, merendah diri, menghargai sesama keluarga dan sekampung,
berbicara jujur, tidak berbuat culas, terhadap isi hatinya”.
Kemudian ia tunduk sembari menangis, Datu Sangiangserri, menenangkan
perbuatannya, Matoa Maiwa, sambil menghempaskan ingus ia berkata
:”Apakah kalian masih ingat ketika pertama kali lahir di Luwu, lalu
terdampar ke Ware’, yang membuatku bersedih, tak dikembalikannya aku ke
dalam, Tuan kita manusia pertama, jelas tidak datang lagi, di dalam
perutnya kembali, sama sepakat, Tuan kita yang wanita yang timbul dari
Busa Empong, turun di Luwu. Itulah yang membuat saya marah, kupergi
membuang diriku. Kubelakangi Luwu, kuterdampar di ware, sampai akhirnya
tiba, di kampung Barru. Tidak ditakdirkan We Tune, To Pabbare-baree,
menjadi manusia di Luwu, menyempurnakan kehidupan kampung, Ware,
mendinginkan orang banyak, Barru telah ditetapkan diberikan untukku,
oleh Tuan kita manusia pertama, yang turun di Luwu, sama sembahnya di
ware. Tidak ditakdirkan We Tune, menjadi datu di Luwu, menjadi Pajung
di Luwu, dan melayanglah sudah, jiwa raga mangkau’ku, sehingga menjadi
padi menguning. Tiga hari setelah aku lahir, di istana kerajannya,
senapati mangkauku, orang pertama di Luwu, yang menetas di bambu betung
(Tellang Pulaweng). Usiaku kemudian pendek, Tuhan telah mentakdirkan,
mati muda di dunia, menjadi Sangiangserri, menjadi padi menguning, pada
perbuatan terlarangku, kubur pembaringanku.
Disakiti aku oleh orang Luwu, itulah yang kusakitkan, kupergi membuang
diri, kubelakangi Luwu, kuterdampar di Ware, kuterdamparlah di Barru.
Sangat takbur nian, orang Luwu dan Ware, aku tidak dinaikkannya,
dirumah peristirahatannya, hampirlah aku jadi benir, di patuk-patuk
oleh ayam, dimakan tikus, baginya lebih berharga, lebih disenangi,
makanan yag salah, dia lebih menyukai, talas dan ubi, sedih nian di
dalam, perasaan hatiku aku pun pergi membuang diri, kuterdampar di
Barru
Belum lagi habis ucapannya, Datu Sangiangserri, matahari pun telah
senja, mereka pun sampai berdesakan, di pinggir kampung, yaitu kampung
Barru, kampung berkelilingnya. Ia pun berdiri mengamati, di muka
rumahnya, Matoa Barru bertepatan sekali, bertutur kata yang baik,
isteri seturunannya, Pabbicara di Barru, seiya sekata semua orang, di
dalam rumah. Terus ia naik, Datu Sangiangserri, di rumah
perisirahatannya, Pabbicara Barru, menyebarkan baunya, memabukkan
harumnya. Laksana angin topan yang datang, begitu kedengarannya, Datunna
Sangiangserri, berdiri bersandar We Datu, pada papan tangga, enggan
untuk naik, keturunan mappajung itu. Maka terasalah di dalam, dalam
hatinya, Isteri Pabbicara, Ia Pun bangkit merangkak-rangkak, Matoa di
Barru, sama berangkat ke belakang, sekeluarga, mengambil air secerek,
menanti baiknya, Datu Sangiangserri, sembari menghamburkan benih, isteri
Pabbiara, menyembah sambil berkata : “Kuru’ Sumange’mu, Datu
Sangiangserri, sangiang yang berdarah biru, keturunan yang disembah,
naiklah kerumah, Datu Sangiangseri, Datu Gandum, Datu Jagung, semua
jelai yang banyak, Datu Meong Palo, Datu Tiuseng, telah terhampar
tikarmu, tikar yang berpinggir laken”.
Lalu di panggillah Bissu, ditudunglah puncaknya, dan dikipas dengan La
Wollo, dan dibunyikan gendang, dan dipukulkan gong, dibunyikan
leang-leang, cacalepa emasnya, seruling yang turun (dari langit),
ramailah kedengaran, upacara datu, keturunan mappajung.
Berdirilah We Datu, dijemput oleh Bissu, dipanggil semangatnya, dan
dihimpun jiwanya, dan di datangkan semangatnya, cahaya semangatnya yang
pudar, keturunan dari Boting Langi’, keturunan di Peritiwi.
Sembah sujud dan berkata, isteri Pabbicara, anak beranak dan suami
(sekeluarga) :”Kuru’ Sumange’mu, keturunan Opu yang disembah, sebelah
menyebelah berdarah murni (maddara takku), naiklah ke rumah, duduk di
singgasanamu, semua padi yang banyak, pada kedudukan kecintaanmu”.
Barulah kemudian naik, Datu Sangiangserri. Maka tampaklah kelihatan We
Datu, menjelma kelihatan manusia, di pandang oleh manusia, Lalu
dicucikan kakinya, baru We Tune’ duduk. Maka serentak pada naik pula,
semua padi yang banyak, semua padi yang setia, gandum, jagung, semua
jelai yang banyak, dan Datunna Meong Paloe.
Sembah sujudlah cepat, isteri Pabbicara, sekeluarga, dan sama-sama
berkata :”Di ataslah engkau duduk, hai keturunan datu yang di sembah,
keturunan yang pantang di durhakai, sangiang berdarah murni, semua
teman-temanmu, di mahligai kemewahanmu, Kuberi engkau kuru’ sumange’mu,
duduklah menetap, menyebarkan keturunanmu di Barru, demikianlah
ketentuan, memberi kehidupan orang bumi”.
Barulah kemudian ia duduk, Datu Sangiangserri, semua hamba
terhormatnya, mendudukan orang yang banyak, memenuhi rumah sepotong
hamba yang diharapkannya, Datu Sangiangserri. Di minyak-minyakilah, dan
didupailah, laksana kabut yang naik, asap kemenyan itu, kemudian di
jamu dengan sirih.
Sembah sujud ia berkata, isteri Pabbicara, sekeluarga :”Duduklah engkau
hai We Raja, di kampungmu di Barru, demikianlah ketentuan, semangat
jiwa ragamu, memberi kehidupan orang bumi. Ku pergi memanggil, semua
penduduk Barru, sebab sudah terlalu lama engkau tinggalkan,
membelakangi kampungmu, pergi tanpa perkataan pulang, haus dan lapar
sudah, pendudukmu di Barru.
Sejak kamu telah pergi, sepanjang jalan, menuruti jalan yang panjang,
melewati perantaraan kampung, tak pernah lagi kembali, datang
Sangiangserri, dan naiklah wisesa itu, di sini di tanah Barru.
Tunduklah tanpa berkata, Datu Sangiangserri, belum lagi hilang
capeknya, Datu Sangiangserri, serentak berdatanganlah, penduduk Barru,
secepatnya pada naik, memuja-muja tak henti-hentinya, di hadapan We
Datu, memberi kuru’ sumange’, Datu Sangiangserri, semua padi yang
banyak, para hamba, Matoa petani memanggil dengan cepat, semua penduduk
Barru.
Belum lagi hancur daun sirih, dan belum sempat mata berkedip, maka pada
berdatanganlah berbondong-bondong, tamu yang banyak, penduduk Barru,
melingkar bak pasar ramainya, Tak henti-hentinya naik, jamu-jamuan We
Datu, belum begitu matang Wisesa, pemberian jamuan dinaikkan oleh orang
Barru. Belum lagi hancur daun sirih, dan mata berkedip, maka
diangkatlah ke luar, jamuan untuk We Datu : lepet jelai, ketupat
gandum, pisang raja bersisir, kelapa muda, tebu yang telah dibersihkan,
nasi ketan berkepal di piring, juga dibuat seperti tiang, dan dibentuk
seperti orang-orangan, diruncingkan puncaknya, bulat seperti bulan
tengahnya, dan ditudungilah atasnya, lalu digantungi emas semua
puncaknya, semua ubi dan talas, penjemput hidangan, untuk Datu
Sangiangserri, semua padi yang banyak, dan Datu Meong Paloe.
Sesudah makan minum, Datu Sangiangserri, maka segera diberi sirih, dan
kembali di dupai, laksana kabut yang mengepul, asap kemenyan,
mengembalikan semua semangatnya, Datu Sangiangserri, menghimpun jiwa We
Datu, duduk bergembira ria, semua teman-temannya, Datu Sangiangserri.
Maka sembah sujudlah berkata, semua penduduk Barru :”Kuru’ sumangemu’,
keturunan opu yang disembah, mangkau’ yang terhormat, seperti aku
diliputi langit, dikasihani Dewata, gembira tak terkira, senangku tak
terukur. Karena pada akhirnya kau kembali, kusandari tak bergoyah,
demikianlah ketentuan di dalam tenggorokanku, bersama-sama kita ke maje
(akhirat), pada hari kemudian”.
Menjawab dan berkata, Datu Sangiangserri :”Dengarlah baik-baik, isteri
Pabbicara, semua orang yang banyak, penduduk Barru, apabila kau
kekalkan, sifat-sifat baikmu, kata-katamu yang tidak bertentangan, di
dalam kampung, itulah yang aku senangi, kembali semua semangatku, maka
itulah satu ampunan, orang yang menerima orang yang kesusahan, menampung
orang yang terbuang, menerima orang yang dibenci, disertai belas
kasihan, orang yang menampung orang terbuang, membawa susah tiada
taranya. Itulah sebabnya kutinggalkan Luwu, kuterdampar di Ware,
kusampai di Maiwa, karena dibencinya kucing, disiksanya kucing, jauh aku
mengembara, hingga tiba di Barru, karena engkau mempunyai sifat
menerima, orang yang kesusahan.
Sembah sujud dan berkata, isteri Pabbicara :”Kuru sumange’mu, keturunan
opu yang disembah, keturunan pajung, Datunna Sangiangseri.
Kehendakmulah We Raja, kepadamulah We Datu, sebab tuanku tahu, kami ini
orang dungunya Dewata, apa kehendak We Datu, itulah yang saya ikuti.
Karena engkau maha pengasih, beritahukanlah aku Puang, ajarkanlah
semuanya tingkah-laku Sangiangserri, kuyakini dengan pasti, di dalam
hatiku, kugenggam tak terlepas, engkau yang tertua sejak awalnya, aku
hanya tua dalam kelahiran”.
Menjawab dan berkata, Datu Sangiangserri :”Baiklah kalau begitu
ucapanmu, dengarlah baik-baik, isteri Pabbicara, semua orang yang
banyak, kalau kau kekalkan, sifat-sifat lembutmu, ucapan yang tidak
bertentangan, sekeluarga dan sekampung, di dalam kampung, benarlah aku
duduk di Barru, demikianlah ketentuan, di dalam kerongkonganmu. Karena
itu kamu orang Barru, janganlah saling bertentangan, sekeluarga dan
sekampung, di dalam kampung, benarlah aku duduk di Barru, demikianlah
ketentuan, di dalam kerongkonganmu. Karena itu kamu orang Barru,
janganlah saling bertentangan! pada sore hari, jangan membesarkan
suaramu! pada waktu tengah malam, jangan besar suara pada subuh hari,
pada fajar subuh, sebab saya terkaget-kaget, iba perasaanku, padam
semangatku. Itu ketika aku berjalan, berkeliling di kampung, mencari
sifat-sifat yang baik, mendengar suara, orang yang berbudi luhur, yang
bagus tutur katanya. Sebab yang selalu kucari, sebagai tempat menetapku,
adalah orang yang mempunyai sifat-sifat yang baik, itulah tempatku
menetap, kampung yang berhati-hati. Tiga kali semalam, aku berkeliling
dunia, jangan sekali-sekali menggemuruh! Memukul timba tempayanmu, kalau
kau menimba air, perbaiki terlebih dahulu! Perasaan hatimu, yang
membuat senang, jangan sekali-sekali padamkan lampumu! Pada tengah
malam, jangan tak menghidupkan! Apimu di dapurmu, tutuplah tempat
berasmu! Kumpulkanlah takaranmu! Itu yang membuat aku gembira, kembali
semua semangatmu, pada malam hari, Jangan sekali-sekali tidak
mengumpulkan! Sajimu bersama sendokmu, kalau kamu tidak mengindahkan,
pantangan wisesaku, sifat-sifat Sangiangserri, ketika aku sedang
bersiap-siap, naik ke tangga, menuju rumah, ketika aku pergi,
mengelilingi kampung, kudapati kalian ribut, di muka dapur, bertengkar
di rumahmu, aku turun kembali. Tiga tahun kemudian, hilang semangat
rezekimu, di dalam dunia, wisesa (bibit) yang kamu tanam. Tidaklah tahu
hal ihwal? Keturunan I La Patotoe, keturunan To Palanroe, menetasnya di
Luwu, anaknya Batara Guru, orang pertama di dunia.
Berkeliling di dunia, menyebarkan baunya, memabukkan harumnya, mencari
sifat-sifat yang baik, diantar oleh rasa kesedihan, pergi kemana-mana,
mencari orang yang penyayang. Ia pun menangis sambil menunduk :”Tahukah
engkau, para penduduk Barru, hambaku di Watampare, saya bersiap-siap,
menuju (naik) ke langit, sebab sudah terlalu perih, perasaan hatiku,
dudukku (ketika menetap) di Maiwa, dibencinya kucing, disiksanya kucing
itu, di pukul siang dan malam, Datu Meong Palo. Seperti diiris
sembilu, perihnya kurasakan, perasaan hatiku, mengingat perbuatannya,
wanita yang durhaka, yang sama semua dalam rumah, laki-laki perempuan,
Itulah yang membuatku sangat sedih, ditendangnya kucing, di atas
tumpukan padi, biarlah aku naik ke langit, aku tak ingin lagi hidup di
dunia ini”.
Serentak sembah sujud dan berkata, isteri Pabbicara, semua orang yang
banyak, penduduk Barru, dan sama berkata :”Kalau memang demikian La
Puang, engkau menuju, naik ke Boting Langi, bawalah aku La Puang, buat
apa aku hidup di dunia, apa yang kita pertahankan di sini, tak satupun,
memberi kehidupan (kami).
Menangis sembari berkata, Datu Sangiangserri :”Kuru’ Sumange’mu, semua
yang menyenangi aku, duduklah engkau marupe, di kampung yang
membesarkanmu. Biarlah sayalah sendiri yang melayang, terus naik ke
langit, pada bambu kehidupanku, senapati mangkaukku, merajuk tak
henti-hentinya, Kecuali tidak diizinkan, duduk menetap di langit,
barulah aku kembali, di Barru, aku akan memilihnya (Barru) sebagai
tempat menetapku, semangat jiwa ragaku.
Sembah sujud dan berkata, isteri Pabbicara :”Kalau memang demikian La
Puang kehendakmu, benar-benar akan naik, melayang di langit, mohon
supaya kembali, di kampungmu di Barru, demikianlah ketentuan, pada
tenggorokan “Menangis dan berkata, Datu Sangiangserri :”Kalau memang
takdir (toto) saya kembali, barulah kita bergembira ria, di mahligai
kemewahanmu, apabila tidak diperkenangkan, orang tua mangkaukku, duduk
dan menetap di langit, berakar di langit, dan sama mengiyalah, semua
penduduk Barru”.
Belum habis ucapannya, Datu Sangiangserri, laksana angin topan yang
datang, begitu kedengarannya, angin ribut tersebut, ketika menuju
melayang, Datu Sangiangserri, menyebarkan baunya, memabukkan wanginya,
kilat sambung-menyambung, diikuti oleh gemuruh guntur. Ketika tengah
malam, ketika bertemunya gelap, saat itulah mereka berangkat, keturunan
To Palanroe, semua padi yang banyak, padi ketan padi biasa, semua padi
yang setia, gandum jagung, semua jelai yang banyak, Datu Meong Paloe.
Pada berangkatlah ia, melayang, Datunna Sangiangserri, semua padi yang
banyak, terus naik ke langit, keturunan pajung. Belum lagi hancur daun
sirih, belum lagi berkedip mata, maka sampailah di atas, pada lapisan
awan. Dan terbukalah kuncinya, pintu langit, dan datang melihat dan
menyaksikan, lapis-lapis langit, terus mereka naik, di Sawo Wero
Pareppa. Mereka akhirnya sampai berdesakan, di muka We Raja, dan sembah
sujud menyembah, dihadapan tuhannya, To Pabbare-baree, di istana
kemewahannya, nenek mankauknya, kebetulan sekali, sedang menampakkan
diri, To Palanroe pada tahta keemasannya, kursi kerajaannya, diliputi
oleh perasaan kasih, sembah sujud dan duduklah, dihadapan tuhannya,
senapati mangkauknya, batara yang melahirkannya, yang menurunkannya ke
dunia, menjadi Sangiangserri, memberi kehidupan orang bumi, Bagaikan
orang yang menimba, madu di dalam hatinya, jiwa keperkasaannya, To
Pabbare-baree, menatap raut wajahnya, keturunan kegembiraannya. Langsung
We Tune duduk, di muka Tuhannya, laksana matahari terbit, mentari yang
mulai muncul, muka yang tidak membosankan, bagaikan bulan yang
sempurna.
Menangislah tersedu-sedu, Datu Sangiangserri, padi ketan padi biasa,
gandum jagung, semua jelai yang banyak, Datu Meong Paloe. Ia pun
berpaling dan berkata, To Pabbare-baree “Kuru’ Sumange’mu We Tune’,
anakku We Maudara (panggilan kesangan Sangiangserri), apa yang
menyebabkan engkau naik? Di sini di Boting Langi, anaknya We nyili’
Timo (ibu Sangiangserri), puteri Batara Guru (Ayah Sangiangserri),
mengapa engkau tidak menetap di dunia? Memberi kehidupan orang bumi”.
Tunduk dan menangislah, Datu Sangiangserri, sembah sujud
berkata:”Sebabnya La Puang, kunaik di Ruwang Lette, sembah sujud
dihadapanmu, kusampai merajuk, saya berkeinginan, kembali masuk, pada
bambu orang tuaku, menjadi darah yang dikandung, senapati mangakaukku,
sebab aku sudah terlalu sakit rasanya, menjadi padi di dunia. Aku tidak
menyukai perbuatannya, tak kusuka sifat-sifatnya, orang dunia orang
bumi itu, aku sudah tidak menggembirainya (menyenanginya), di
sepak-sepak aku burung pipit, diisap langau, dilejit oleh tikus,
bisa-bisa aku jadi benir. Mereka tidak lagi menjaga aku, juga tidak
berpantang lagi, pantangan wisesaku. Tidak seia sekata, orang di dalam
dunia, orang di dalam kampung, jauhlah diperkatakan, orang di dalam
rumah, merekapun menusukkan tongkatnya, makan yang bukan makanannya,
orang dunia orang bumi itu”.
Memasukkan larangan pergaulan, orang yang muda menyiksa, perempuan yang
bersalah, itulah yang membuatku bersedih, ibah lah hatiku, hilang
semangatku, tersingkap jiwa ragaku, juga di dalam, perasaan hatiku, Aku
sangat benci, dibencinya kucing, disiksa kucing itu, dipukul siang
malam, sebab hanya dialah La Puang, kuharapkan menjagaku, mengembalaku
menjagaku, siang dan malam, justru dialah yang dibenci, dipukul tak
berantara, ketika aku tinggal di Maiwa, Sebab cukuplah Tuhan, perihnya
perasaanku, tak dapat lagi La Puang, aku kembali ke dunia, berkembang
biak di dunia.
Orang tidak lagi menghargai diriku, akupun sudah tidak menggembirainya
(menyenangi), dilaksanakannya semua pantanganku, sifat-sifat wisesaku,
pabbicara yang culas, serta raja yang tidak jujur.
Ia pun tunduk menangis, To Pabbare-baree, menjawab dan berkata : “Kuru’
Sumange’mu, kur jiwa kesayanganku, seluas langit pusakamu, marahkah
engkau La Wija? (keturunanku)? Meraju kah gerangan engkau We Datu,
merayu-rayu tak henti, anakku We Maudara, sehingga engkau naik ke
langit, di kampung kediamanmu, di tempat dibesarkannya, senapati
mangkaukmu. Lalu bagaimana anakku We Maudara, kalau kamu merenguk
terus, tak mau lagi menjadi orang bumi, hancurlah sudah, orang bumi
itu, semua orang akan mati, semua yang ditutup di langit. Aku tak tahu
lagi bagaimana harus menjawabmu, aku tak bisa lagi membantumu, anakku
Sangiangserri, ketika kamu merajuk di sini, di Sawo Wero Pareppa, pada
perbuatan pantangan Tuhanmu, bambu kelahiranmu. Karena memang di
sanalah menetap, semangat jiwa ragamu, penahan jiwamu, ibu mangkaukmu,
Batara yang melahirkanmu, di atas di Coppo Meru, sampailah engkau
merajuk, sebab keinginanku, di dalam sanubariku, aku ingin kau tetap
menetap, hidup di dalam dunia, di dunia mengembangkan turunanmu”.
Merunduk sembari menangis, Datu Sangiangserri, belum lagi lepas
pembicaraan, To Pabbare-baree, ia pun berpaling menendang, jalan yang
menuju, di kampung Coppo Meru, ditiupnya tiga kali, keturunan
kegembiraannya, tak terasa dirinya, Datu Sangiangserri.
Ia pun berdiri maju, di kampung Coppo Meru (alam arwah) , tempat
menetapnya, ibunda mangkauknya. Ia pun berpaling melihat, Batara yang
melahirkannya, suami isteri, tak ubahnya orang yang saling diselipkan,
jiwa raganya, senapati mangkauknya, Datu Sangiangserri, menatap
anaknya. Lama kemudian baru Opu Batara Luwu berpaling, menangis sembari
berkata, Datu yang tercinta :”Kuru sumange’ mu, anakku Sangiangserri,
ada apa gerangan kamu naik, di Sawo Wero Pareppa? Mengapa tidak menetap
saja di dunia, memberi kehidupan orang bumi”.
Secepatnya sembah sujud, Datu Sangiangserri, lalu bangkit duduk, di
mahligai We Datu, yang bersegi tiga kemilaunya, serentak berdiri pula,
semua temannya, hamba sesama terbuang, Datu Sangiangserri.
Sembah sujud dan berkata :”Itulah sebabnya La Puang, ku naik di Boting
Langi, ku sampai di Coppo Meru, ku tiba berdesakan, di Sawo Wero
Pareppa, Aku tak mau lagi duduk (menetap) di dunia, memberi kehidupan
orang bumi, tak dapat lagi aku menjadi orang bumi, aku rindu kamu
kembalikan, masuk kedalam rahim, aku tak suka perbuatannya, tak kusukai
sifat-sifatnya, orang bumi itu. Musnah gerangan We Tune, duduk di
kampung dunia, aku hanya tinggal di bumi, di patuk-patuk ayam, dilejit
oleh tikus, di habis-habisi oleh burung pipit, diisap oleh langau,
dililit oleh ular, dimusnahkan oleh ulat, bisa-bisa aku jadi benir,
Mereka tidak lagi mau menungguiku, Halnya kucing, kuharap menjagaku,
mengembalaku, menjagaku, siang dan malam, justru dialah yang dibenci,
dipukul tak berantara, oleh isteri kecintaannya, matoa petani itu, yang
berkuasa di Maiwa. Itulah yang kubenci, perihku tak terucapkan, ku
langsung menuju, naik di Boting Langi, memegang lama La Puang, kamu
benarkan kepedihanku”.
Tunduklah ia menangis, ibunda mangkaunya, Datu Sangiangserri, sembari
berkata :”Kasihani aku We Tune’, turunlah kembali! Menghadirkan diri di
dunia, memang demikianlah takdirmu, dari to Parampu’-rampu’e, ketika
kamu diturunkan ke bumi, memberi kehidupan, pada tenggorokannya,
manusia di dunia dan di bumi. Dan bisalah semua orang, anakku We
Maudara, semua keluargamu. Duduklah engkau di dunia! Mati semua We
Tune, semua yang di tutup langit, kalau engkau tetap menetap di sini,
di kampung Coppo Meru, Sebabnya saya naik, di Sawo Wero Pareppa, sebab
telah padam, semangat jiwa ragaku, pupuslah sudah jiwaku, padam bagai
pelita, jiwa ragaku. Izinkanlah aku di sini, di kampung Coppo Meru,
negeri hari kemudian, di sini padang yag luas.
Tak tahukah engkau, bahwa telah berpindah di hari kemudian, Batara yang
melahirkanmu. Kasihanilah aku We Tune’, anakku We Maudara, turunlah
cepat, di kampung orang dunia, memberi kehidupan orang bumi, karena
demikianlah ketentuan, di dalam tenggorokan, orang dunia orang Bumi”.
Sembah sujud dan berkata, Datu Sangiangserri, sembari menangis
tersedu-sedu :”Kasihanilah aku La Puang, turutlah rajukanku. Biarlah
kita mati bersama, kembali di hari kemudian, kulaksanakan semua
pantangan, di kampung Coppo Meru, ataukah di Sawo Wero Pareppa. Biarlah
ku tinggalkan, kubelakangi dunia, dari pada tinggal di dunia, berakar
di Watampare’, kudengar tak kudengar, melanggar pantanganku. Sesuatu
yang sangat tidak kusukai, berbicara takabbur,orang dunia itu, jelaslah
sudah La Puang, tak senang dengan diriku, saya juga sudah tidak
menyenanginya. Apa saja yang terbaik, ku naik La Puang, agar supaya
engkau mau, memasukkan aku kembali, masuk di dalam rahim. Tak dapat
lagi aku menjadi orang bumi, aku tidak menyukai sifatnya, juga
perbuatannya, orang dunia orang bumi itu.
Biarlah mati semua, apalagi yang harus ku ambil pulang, kembali di
dalam dunia, di patuk-patuk ayam, di lejit tikus,hampir saja aku
menjadi benir, dililit ular. Tidak mau lagi menjagaku, dikerjakannya
semua pantanganku, pantangan wisesaku, tak ada lagi yang dapat
kupertahankan, semangat jiwa ragaku.
Pedihku tak terkira, dipukulnya kucing, dipukul siang malam, Padahal
Cuma kucing itulah, kuharap menjagaku, menyempurnakanku dan
membesarkanku, menjagaku dan mengawalku, tanpa tidur, pada siang hari.
Justru dialah yang dibenci, Datu Meong Palo, pada isteri kecintaannya,
matoa petani, yang berkuasa di Maiwa. Itulah yang kusakitkan, pedih tak
terperikan. Maka berangkatlah aku, pergi membuang diri, jalan
menelusuri takdir, mencari sifat-sifat yag baik, menelusuri jalan yang
panjang, hingga akhirnya aku sampai di Barru. Kusinggah mengamati, dan
dari situlah aku menuju, di tempatnya, Pabbicara Barru, naik kelangit
ini.
Aku ingin kembali, masuk ke dalam rahim, menjadi darah kau kandung, di
dalam perut, tak usahlah saya menetap di dunia, merasakan semua, semua
yang merayap dan semua yang terbang, semua yang di tutup langit”.
Bagaikan orang yang diselipkan, perasaan hatinya, Opu Batara Luwu,
bagaikan pupus di dalam, perasaan hatinya, mendengar ucapannya, isi
perutnya. Tiga hari ketika ia lahir, padam semangatnya (meninggal),
semangat mangkau’nya, di kampungnya di Luwu. Tapi dilanggar
pantangannya, pantangan wisesanya, Anak perempuan diciptakan, bagaikan
matahari bersinar, bulan bersinar, kelihatan jelas, anak kecintaannya,
yang kemudian sama padam (meninggal), semangat jiwa raganya, tertegun
(tagalatta), dia melihatnya, kecantikan kecintaannya, bagaikan bulan
sempurna (seppulo eppa ompona ketennge), lemah lunglai di dalam,
perasaan hatinya, Batara terhormatnya Luwu, rindu di anaknya, orang yang
korban, tenggelam, menjadi Sangiangserri, duduk sendirian, dimasukkan
ke dalam dunia.
Ia pun berpaling dan berkata, senapati ibundanya, Batara Sangiangserri
:” Tak ubahnya kecantikannya, anak kecintaan mangkau’nya, kembar emas
yang dipandang, tuhan kita Patotoe, dan perempuan, sama kecantikannya,
tuhan kita Palinge, tidak tinggal begitu saja, anak kecintaan
mangkau’nya, tak ada duanya kecantikannya, di dalam dunia, bercahaya
benar rumah, menyinari rumah, bagai bulan bersinar, matahari yang mulai
terbit, berkilaupun mata memandangnya, roman muka kecintaannya”.
Kemudian ia tunduk dan menangis, menepuk dada tak henti-hentinya Batara
yang melahirkannya, Datu Sangiangseri, sembari berpaling dan berkata
:”Kuru’ Sumange’mu We Tune’, anakku Sangiangseri, merajukkah engkau
gerangan, juga bersitegang, merajuk tak henti-hentinya, tapi apalah
dayaku, kali ini aku tak dapat menuruti, rajukanmu, dua kalikah engkau
diciptakan? Melewati jalan yang sempit? Menjadi darah ku kandung? Sebab
engkau tak diizinkan, hidup menetap di langit, juga tak boleh We Datu,
dikembang-biakkan (pabbija) di Batara (langit), memang kau hanya
diciptakan di dunia, untuk menjadi Sangiangserri, memberi kehidupan
orang bumi, memang demikianlah takdirmu, dari To Parampu’-rampu’e”.
Tunduk dan menangislah, Datu Sangiangserri, begitu deras mengalir air
matanya, sembari sembah sujud dan berkata :” Aku benar-benar sudah
tidak mau, kembali ke dunia, biarlah aku pergi, membuang diri La Puang.
Biarlah orang dunia itu, merasakan sakitnya, mau mati orang dunia itu,
atau musnah orang bumi itu, biarlah semuanya menyeberang, kembali di
dunia dan hari kemudian, membuka perkampungan dimana, tenggorokannya,
orang dunia durhaka itu, tidak seimbang, hati sanubariku, hidup
dibuatnya menderita. Ketika aku lagi nyenyak tertidur, ia naik
menendang, Datu Meong Paloe, di puncak tumpukan padi, kubangun
awut-awutan, lemah lunglai di dalam, perasaan hatiku, dikagetkannya
aku, isteri kecintannya, matoa petani, yang berkuasa di Maiwa.
Apakah engkau lebih memilih dia La Puang, dari pada anak kandungmu,
orang keturunan bersalahmu, menjadi Sangiangserri aku benar-benar sudah
enggan kembali, di dalam dunia”.
Sejenak ia tunduk dan menangis, Batara tunggalnya Luwu, mengusap-usap
(kepala) anaknya, diminyakinya kembali, di dupailah segera, sembari
memberinya pakkuru’ sumange’, isi perutnya (anaknya), laksana kabut
yang mengepul, sirih lengkapnya Puange, yang timbul di Busa Empong.
Ia pun berpaling sambil berkata, Opu Batara Luwu :” Kasihanilah aku We
Datu, anakku We Maudara, turutlah diturunkan, menjelmakan diri di
dunia, untuk menetap di sana We Tune’, duduklah kembali di Luwu, di
tempat dibesarkanmu, di kampung yang dikuasai, Batara yang
melahirkanmu”.
Sembah sujud menangis, Datu Sangiangserri, menyembah kedua belah
tangannya dan berkata :” Kubuka kedua belah tangan ku La Puang,
kusembah semua ucapanmu, aku tidak mau lagi kembali ke Luwu, Mereka
lebih menyukai sagu, lebih menyukai dan mengutamakan, dari pada diriku,
dia tidak mengetahui dirinya, orang Luwu dan Wara’ itu, keturunan La
Patoto, tunasnya La Palanroe (Batara Guru), yang menetas di bambu
betung, anaknya (pattolana) We Nyili’ Timo, yang muncul dari busa air.
Membawa kepedihan yang besar, dan kesedihan yang tiada tara. Karena
dibencinya kucing, Datunna Meong Paloe, sampai akhirnya aku pergi
membuang diri, kubelakangi Luwu, dan terdampar di Maiwa”.
Menjawab dan menangislah, ibunda mangkau’nya, Datu Sangiangserri :”
Bagaimana gerangan perbuatannya, orang yang tak mengenal tuhannya, yang
sengsara yang besar, melahirkan anaknya. Tiga hari kemudian, maka
padamlah nyawanya, dan tiga hari kemudian, kuziarahi kuburmu, kudatangi
padi yang menguning, berkumpul dan berhimpun, gandum dan jagung, semua
jelai yang banyak, kunaik di Boting Langi, menyampaikan kepada tuhan
kita, To Pabbare-baree, dan jawabnya :” Itulah anakmu, menjadi padi
menguning, menjadi gandum dan jagung, menjadi jelai yang banyak, jangan
sekali-kali engkau memakannya ! anak kecintaanmu, sebelum lepas La
Bela, tiga tahun meninggalnya, masuknya di dalam perut”.
Sembah sujud dan berkata, Datu Sangiangserri :” Bukan La Puang,
menyebabkan aku meninggalkan Luwu, dan kutinggalkan Wara’, di negeri
kekuasaanmu, engkau masukkan aku, di dalam tenggorokan, justru itu La
Puang, kutinggalkan Wara’, karena benciku yang tiada tara, marahku yang
marah betul, karena tidak dinaikkannya aku, ku duduk La Puang, di
perantaraan kampung, dimakan tikus, di patuk-patuk burung, hampir saja
diriku jadi benir, itulah yang membuat aku marah, kupergi membuang
diriku, mengelilingi dunia ini”.
Kembali tertunduk dan menangis, Datu Sangiangserri, menangis
tersedu-sedu, deras mengalir, air matanya, mendengarkan
ucapan-ucapannya, senapati mangkau’nya, lama ia dibujuki, dibelai-belai
dan di usap-usap, dan diminyaki, kemudian di endapkan, minyak wangi
yang harum baunya, barulah kemudian, merasa enak perasaan hatinya, Datu
Sangiangserri.
Menjawab berkata : “Duduklah engkau La Puang, di mahligai istanamu,
sekeluarga, kuberi engkau semua makanan, semua isi istana, terhadap
orang yang berpisah jiwanya”.
Dan serentak mereka berkata :”Peganglah erat-erat jiwa datumu, anakku
We Maudara, kembali, ke kampung dunia, memberi kehidupan orang bumi,
demikianlah ketentuan, berakar menyebarkan keturunanmu”.
Menjawab dan berkata, Datu Sangiangserri :” Biarlah aku turun kembali,
dan yang kupilih untuk kutinggali, adalah yang sesuai dengan kata
hatiku, jujur dan tidak pelit, terhadap sesamanya manusia, tidak
berbuat culas, di dalam hatinya, tidak cemburu hati, terhadap sesama
manusia, tahu menghargai wisesa, menaikkan Sangiangserri, Apabila saya
tidak menemukan orang yang baik hati, aku kembali kelangit, kita
bersama-sama La Puang, yang telah ditentukan”.
Serentak ia tunduk menangis, ibu mangkau’nya, begitu deras mengalir,
air matanya, duduk saling bertangis-tangisan, anak kecintaan
kesayangannya, mendengar ucapan-ucapan, isi perutnya (anaknya),
merenungi nasib (toto) anaknya.
Ia pun berpaling berkata, Opu Batara Luwu, sembari menangis
tersedu-sedu, mengusap-usap anaknya :”Kuru’ Sumange’mu, anakku We
Maudara, kasihani aku We Tune ! perbaiki, perasaan hatimu, kembali
menjadi orang bumi, kau telusuri takdirmu, yang telah ditentukan, To
Pabbare-bare’e. Sebab menurut firasatku, tidak enak perasaanmu,
memabukkan baumu, makanannya orang dunia, Peganglah jiwa datumu !
anakku Sangiangserri”.
Belum lepas ucapannya, Batara tunggalnya Luwu, dibenarkan ucapannya,
senapati mangkau’nya, sambung-menyambunglah bunyi guntur,
sabung-menyabung kilat, turunlah pergi We Datu, berpegang erat pada
guntur, berpautan dengan kilat, dipikul dengan udara, bertelekan pada
tanah, menyeimbangkan badan pada angin, Serentak mereka berangkat,
semua teman-teman, hamba datu pengawalnya, mengikutinya turun ke bawah,
Datu Sangiangserri. Bagai akan musnah langit, dan patah batara
(langit) itu, bergetar peretiwi, bagai hancur tanah, di bawah di dunia,
sebagai pertanda menuju, kembali di dunia, anaknya Batara Guru,
anaknya We Nyili’ Timo, yang menetas, pada bambu petung, dan yang
muncul di busa air.
Bagaikan akan menghilang tanah ini, bagai akan tercabut tanah ini,
serentak orang-orang dunia berkata, orang di bawa batara :” Siksaan apa
gerangan, dari To Pabbare’-baree, begitu berat kedengaran, goyangan
langit itu, peretiwi di dengar, bakal hancur dunia ini, karena kerasnya
suara guruh itu “
Begitulah tandanya, menuju, turun kembali, Datu Sangiangserri,
berhamburan manusia, di kampung dunia, orang yang di benua bawah,
Bagaikan akan pupus, perasaan hatinya, Opu Batara Luwu, melihat
anaknya, di terpa sinar matahari, duduk dia bersandar, mengamati
anaknya, berpegang pada petir, berpaut pada guntur, melewati
celah-celah awan, berkilauan di pandang, mentari yang mulai bersinar,
matahari yang mulai naik, cahaya kilat bersinarnya. Tertegun
(tagalatta) di dalam, perasaan hatinya, Opu Batara Luwu, melihat
kecantikan isi perutnya, menjadi Sangiangserri.
Ia pun berpaling dan berkata, Opu Batara Luwu, pada isteri kecintaannya
:”Lebih baik kita turunkan sekarang, angin ribut kebencian, dan
dimusnahkan Maiwa, dan dipindahkan semua, reruntuhan negeri di dunia,
orang bumi yang durhaka, sampai kepada yang tidak mengenalnya, keturunan
I La Patoto, di atas di Ruwang Lette”
Maka disiksalah semuanya, semangat jiwa raganya, orang yang membenci
kucing, menyiksa kucing, Datu Meong Paloe, dan dimusnahkan juga
semuanya, orang dunia orang bumi, yang memasukkan (melanggar)
pantangan, pantangan pemali wisesa. Dan yang menusukkan tongkatnya,
perempuan bersalah, pabbicara yang culas, raja yang tidak jujur, orang
yang cemburu hati terhadap sesamanya manusia.
Sebab terlalu sakit hatinya, menyaksikan anaknya menderita, isi
perutnya. Tidak enak perasaannya, di dalam hati sanubarinya, mendengar
perbuatan, matoa petani, penguasa di Maiwa, Maka berdatanganlah,
binatang-binatang yang banyak, penyiksaan yang tidak ada duanya. Dan
diturunkan pula, penyiksaannya yang kuat, kampung di Maiwa, semua
kampung yang pernah diinjak, Datu sangiangserri, semua kampung yang
disinggahinya, menepakkan pikiran, terbakarlah sudah, dan menjadi
debulah, kampung Maiwa, hancurlah kampung Kessi, rubuh pulalah Lisu,
menjadi debu tak muncul, kampung di Watu, semua kampung yang dilewati,
Datu Sangiangserri, bersih laksana lautan, kampung Langkemme.
Tunduk sembari melihat, Datu Sangiangserri, dipindah-pindahi negeri
lain. Dan bergetarlah ia menyaksikan, perasaan hatinya di dalam,
sembari berkata, didalam hatinya :” Di dahului betul aku, penyiksaan
yang diturunkan, ibu mangkau’ku, barulah aku yakin, sudah teguhlah di
dalam perasaan hatiku”
Terus-terus ia pun turun, Datu Sangiangserri, dan tengah malam, ia pun
tiba berdesakan, di kampung Barru. Sebab memang telah siap, pabbicara
di Barru, menunggu kembalinya, Datu Sangiangserri, Isteri pabbicara,
sekeluarga, memberi kuru’ sumange’, keturunan pajung itu, sembari
meneburkan bertih tak henti-hentinya, berbunyilah penutup sirih,
menarilah para bissu (maujangka), bissu yang turun langsung dari
angkasa, pergi melengkapi, bawaan orang boting langi’, dituntun oleh
peritiwi, mengusung We Datu, Datu Sangiangserri.
Berdirilah merangkak-rangkak, isteri pabbicara, menimba air secerek,
baru kemudian ia duduk, menghadapi pelita, sekeluarga, di sebelah
selatan dapur, menunggu We Tune’.
Naiklah merangkak-rangkak, bissu langsung dari langit tersebut,
menggantungi La Wollo, menabur bertih tak henti-hentinya, menghamburkan
cucubanna, dan memberi kuru’ sumange’, Datu Sangiangserri, semua padi
yang banyak, Datu Gandum, Datu Jagung, semua jelai yang banyak, Datu
Meong Paloe.
Serentak mereka terangkat, diarak dengan tenang, dan dibunyikanlah
galappo, dikipas dengan La Wollo, dan yang ditempuh naik, di istana
kerajaannya, pabbicara di Barru, kemudian dicucikan kakinya, Datu
Sangiangserri.
Sembah sujud dan berkata, isteri pabbicara :”Kuru’ sumange’mu,
keturunan opu yang disembah, sebelah menyebelah berdarah murni (maddara
takku’), di atas gerangan engkau duduk, di istana kedudukanmu, semua
yang menyenangimu. Kuru’ Sumange’mu, kur jiwa kecintaanmu, keturunan
opu yang disembah, keturunan orang yang di durhakai, sebelah menyebelah
berdarah murni, semua telah siap, tempat tertegun (tagalatta) jiwamu,
seluas langit pusakamu, tempat tertumpunya jiwamu, perilaku wisesa,
agar senang perasaanmu, perasaan hatimu, semangat jiwa ragamu, agar
supaya dapat menetap, jiwa sanubarimu, di kampungmu di Barru”
Barulah dia perdi duduk, Datu Sangiangserri, semua padi yang banyak,
memenuhi rumah sepotong, Kemudian diminyaki cepat, lalu diberi sirih,
Datu Sangiangserri. Sembah sujud dan berkata, isteri pabbicara, sembari
berpaling menaburkan bertih :”Kur jiwa semangatmu, karena kau tetap
kembali di sini, demikianlah ketentuan, berakar menyebarkan keturunan,
di Kampung Barru”
“Menjawab dan berkata, Datu Sangiangserri :”Mudah-mudahan abadilah,
hati baikmu, jujur, berhati-hatimu. Demikianlah pula semua sesamamu,
karena sifat penyayangmu, menerima orang yang terbuang, menampung orang
yang kesusahan, supaya tidak kemana-mana, mencari sifat-sifat yang
baik, terbuang dan terdampar, di kampung yang jauh, sampai akhirnya aku
tiba, pada tempat dibesarkannya, saudaraku di Barru. Karena adanya
sifat pengasihmu, biarlah aku menetap di Barru, mendengar dengan
seksama, kata-kata yang baikku. Agar supaya engkau juga memahami dengan
baik, pantangan wisesa, anak cucumu, sahabat-sahabatmu, semua yang
menyenangiku, penduduk di Barru”
“Dengarlah baik-baik ! pesan dan petunjuknya, nasehat baiknya, nenek
mangkau’ku, Batara yang melahirkan aku, pembuluh rahim, Opu Batara
Luwu, orang pertama di Wara’, yang muncul di busa air, yang menetas di
bambu betung. Ketahuilah We Tune’, To Pabbaree-baree, janganlah kamu
kasar mulut ! pada waktu tengah malam, jangan besar suara! Pada
bertemunya gelap, pada subuh hari, jangan juga marupe’ ! kamu menyaji
nasimu, kalau belum begitu lurus perasaan hatimu, jangan berkata-kata !
kalau kamu sedang makan, sebab terkaget-kaget, di dalam hati
sanubarimu, jangan engkau menyaji nasimu ! kalau belum kamu cuci !
tangan dan sendokmu, sebab kalau demikian, seperti kurasakan, orang
yang diiris sembilu, di dalam tenggorokanku, bagai akan lenyap,
semangat jiwa ragaku”
“Kecuali marupe’ kamu meninggalkan semua pantanganku, menjauhi semua
pemaliku, barulah aku menetap, penguat semangatku, untuk menetap di
Barru”
“Jangan pula marupe’, menakari nyirumu, jangan engkau menurunkan,
takaranmu dari rumah, melayang semangatku, dan tersentak jiwa ragaku”
Sembah sujud berkata, isteri pabbicara :” Janganlah demikian We Datu,
tuhan kita pemilik semua di kedalaman (dasar laut), keturunan yang
berdarah murni (maddara takku), sebelah-menyebelah yang disembah. Kur
semangatmu, segala keingianmu La Puang, kusandari tak tergoyahkan,
kusebut-sebut kemana aku pergi, di kampung Barru”
Menjawab berkata, Datu Sangiangserri :” Syukurlah karena kamu mau,
isteri pabbicara, menyenangi diriku, dengarkan baik-baik ! nasehat
petunjukku, jangan sekali-kali !! engkau tak menghidupkan, apimu di
dapurmu, juga jangan marupe’, kamu kosongi periukmu, begitu pula tempat
berasmu, tempat bakul berasmu, juga marupe’! jangan kau kosongi
tempayanmu, air yang kau inginkan, kamu hidupkan pelita, segenggam
panjangnya, pada malam jumat”
“Hai sekalian orang Barru, jangan menukarkan, saji dan sendokmu, di
belanga dan periukmu. Sebab kalau demikian marupe’! tidak mau
berhati-hati, segala pantangan wisesa, habislah aku dimakan ulat, juga
bakalan aku jadi benir, dimakan langau, dipatuk-patuk burung pipit,
dimakan oleh tikus, dibelit aku ular, Tak dapat lagi aku hadir
(berhasil), apabila kamu tidak menyayangiku, ketika aku turun di bumi,
yang akan diwarisi oleh orang belakangan”
“Jangan juga marupe’ berbuat yang culas, jangan sekali-sekali ! hatimu
tidak jujur, mengambil yang bukan menjadi hakmu (milikmu), memakan
sesuatu yang tidak baik asalnya, memakan dengan menelan-nelan
(berbunyi), di muka dapur. Yang aku senangi, berkumpul semua
semangatku, kalau kamu meninggalkan semua pantanganku, sebaliknya yang
paling kusakitkan, orang yang salah niatnya, terhadap anak cucunya,
begitu pula orang yang berbuat zina, tidak bakal berhasil padi”
“Kamu sekalian orang Barru, kalau benar kamu mau, senang pada pada
diriku, gembiraku tak terkira, karena engkau dapat marupe’,
meninggalkan semua pantanganku, sampai menyembah, di atas di Boting
Langi, di bawah di Peritiwi”
Sembah sujud berkata, isteri pabbicara, dan orang yang banyak :”
Tandailah dengan baik, duduk (menatap) bergembira ria. Sebab menurut
kata hatiku, di dalam sanubariku, betapa gembiranya aku La Puang,
sampaikanlah dengan jelas !kabarkanlah kebaikan, larangan wisesae, dan
pemali Sangiangserri, apa kata We Tune’, Datu Sangiangserri”
“Engkau sekalian orang Barru, semua orang yang banyak, dengarlah
kataku, dengarlah dengan jelas ! adat istiadat Sangiangserri, ajarannya
tadi, nenek mangkau’ku. Apabila kamu menyiapkan kataku, dengarlah
dengan jelas! Adat istiadat Sangiangserri, ajarannya tadi, nenek
mangkau’ku. Apabila kamu menyiapkan aku, menyiapkan bibit padimu,
duduklah menghadapi pelita, berjagalah (maddoja) marupe’, juga semua
gerakan hati sanubarimu (ati macinong), juga ucapan-ucapanmu, juga
pandangan matamu, musuhlah nafsumu, batasi amarahmu, bendunglah air
liurmu (keinginan), kemudian menghadap dengan baik, hatimu kepada
Tuhanmu, hatimu memohon rasa kasih (rahman), dari To Pabbare-baree,
sabarlah engkau dengan penuh kepasrahan, terhadap sesama dicipta.
“Engkau sekalian orang Barru, tutuplah tempat berasmu, jangan
sekali-kali kosong, beras pada bakulmu, kumpulkanlah semua takaranmu !
membereskan semua sajimu, demikian pula sendokmu, hati-hati jangan
sampai jatuh”
Jangan kasar mulut ! terhadap sesamamu manusia, jangan juga kamu
melakukan ! berkumpul-kumpul berlebihan, pada sore hari, dan tengah
malam. Jangan juga marupe’! duduk berdempet-dempetan, di muka dapur,
memperebutkan puntung kayu, jangan bertengkar, pada subuh hari, pada
pagi hari, jangan sekali-kali bergemuruh, engkau memukul tempayan.
Hati-hatilah pelitamu, wisesa (bibit) yang kau persiapkan, tiga kali
semalam, engkau mengepulkan asap kemenyanmu, sirih lengkapmu We Tune’,
Kudapati engkau ribut, marah di rumahmu, pilulah jiwaku, tersengat jiwa
ragaku, hilang semangatku, tertegun sanubariku. Tidak jadi bibitmu,
bibit yang kau persiapkan, hayatilah dan laksanakanlah, pantangan
wisesaku.
Apabila engkau sekalian, isteri-isteri di Barru, mendengar semua
nasehat , menjauhi semua larangan, pantangan wisesae, mudah-mudahan
engkau beruntung, besar tak terhalang, hidup menyebarkan keturunan,
semua bibit yang kamu tanam.
Apabila telah sampai, waktunya kami tuai, segenggam saja sehari,
barulah kamu ikat, kamu isi padimu, di tengah-tengah sawah, jangan
sekali-kali kamu cadingi ! sebab itu dilarang, oleh nenek mangkau’ku.
Tidak baik dilakukan, barang yang di tuai malam, haram diisikan, pada
tempat beras, tidak mendatangkan (hasil), wisesa Sangiangserri.
Itulah yang kusampaikan kepadamu, isteri pabbicara, semua orang yang
banyak, tiga kali aku semalam, mengelilingi kampung, mencari perbuatan
baik, baru aku kembali, pada rumah tempat menetapku. Apabila
kudapatkan, ketika menanjak naik ke tangga, aku mendengar, mulut kasar,
aku akan turun kembali, dan seterusnya pergi membuang diri. Dan yang
kupilih sebagai tempat menetap, adalah orang yang sesuai dengan kata
hatiku, sabar berpasrah diri, jujur dan hati-hati, terhadap sesama
manusia.
Jangan berselisih faham, sekeluarga dan sekampung, sebab aku
terkaget-kaget, di dalam sanubariku, hilang semangatku. Demikianlah
moga-moga engkau pengasih, seiya sekata, terhadap seisi kampung,
sampaikanlah dan nasehatlah pula, semua penduduk Barru”
Sembah sujud berkata, isteri pabbicara : ” Kur semangat jiwamu,
keturunan opu yang disembah, sebelah menyebelah berdarah murni, anak
yang pantang di durhakai, Datu Sangiangserri, semua padi yang banyak,
Datu Gandum, Datu Jagung (baralle), Datu Meong Paloe. Akan ku usahakan,
menghindari semua laranganmu, menjauhi semua pemalimu, karena rasa
pengasihmu, mau menetap di Barru, sampai bersama mati, bersama ke
akhirat (ri maje), apa yang menjadi keinginanmu We Raja, dan perkataan
mu We Datu”
Menjawab berkata, Datu Sangiangserri :”Baiklah kalau begitu katamu,
hanya langit di atasmu, ucapan rendah dirimu kasihanilah aku,
persiapkanlah dengan baik ! naik ke rakkeyang, rakkeyang istanaku”
Berdirilah merangkak-rangkak, isteri pabbicara. Diminyakinya cepat,
dihambur cucubanna, dan diberinya kur sumange’, di dupai berangkat, dan
dikipaskan dengan La Wollo, dan yang dilewati naik, Datu
Sangiangserri, semua padi yang banyak, Datu Meong Paloe.
Sambung-menyambung kilat, dan bergemuruh guntur, dan serentak
berdirilah, semua padi yang banyak, diantar oleh angin yang ribut, di
bawa-bawalah oleh petir, di arak oleh guntur geledek, memegang pada
kilat itu, bergenggam pada guntur, diarak dengan tenang, oleh
teman-temannya, sampai terlihat duduk dengan tenang, di rakkeyang.
Belum hilang lelahnya, Datu Sangiangserri, ia lalu berpaling dan
berkata, kepada teman-temannya :” Sudah tujuh malam We Tune’, ketika
tibaku dari langit, lalu aku terangkat, naik di rakkeyang, rakkeyang
istanaku, belum pernah aku mendengar, pembicaraan yang berselisih, di
dalam kampung, bakal menetaplah aku. Demikianlah ketentuan, berakar
menyebarkan keturunan, memberi kehidupan orang bumi. Apabila ia
mengabadikan sifat-sifat baiknya, kata-kata lemah lembutnya, seiya
sekatanya, isteri pabbicara, semua orang yang banyak, maka
berkepanjanganlah aku bersamanya, duduk bergembira ria dalam suka cita.
Kalau tidak ada halangan, disetujui, langitku (Tuhannya di langit), dan
diliputi oleh Peritiwi (Tuhannya di Peritiwi), nenek mangkau’ku,
batara yang melahirkanku, aku berniat menaikkan, wisesaku pada tiap
rumah, di kampung Barru, terhadap semua orang yang menyenangiku”
Serentak sama naiklah, isteri pabbicara, semua orang yang banyak
(rakyat), begitu mendengar ucapan, Datu Sangiangserri, keturunan
pajunge. Sembah sujud secepatnya, menghamburkan cucubanna, sembari
menaburkan bertih berkata :”Kur jiwa semangatmu, keturunan opu
mangkau’, anak yang pantang di durhakai, sangiang yang berdarah murni,
itulah semua sesamamu, karena keinginanmu menetap, di rakkeyang
istanamu, ketentuan menetaskan keturunan, memberi kehidupan orang bumi.
Ku panggil semuanya, penduduk Barru, yang mau berpantang, dan menjauhi
semua, semua pesan-pesan We Raja, Datu Sangiangserri”
“Hai sekalian orang Barru, janganlah menampung, orang yang tidak baik
perbuatannya, engkau semua pabbicarae, berbicaralah dengan jujur, sebab
tidak baik jadinya, bisesa Sangiangserri (bibit padi), yakinilah semua
! petunjuk dan nasehatnya, pantangan-pantangan dari langit ! kubawa
turun (ke bumi) menjelmakan diri di dunia. Ketahui dan yakinilah !
pabbicara (hakim) yang jujur, nanti kamu menjalani, benarkanlah sesuatu
yang salah, barulah engkau menyalahkannya. Hadirkanlah saksinya
(sabbi), saksi dari kedua belah pihak, dan alat pengukurmu telah
mengiya, hatimu telah membenarkan, di dalam sanubarimu, barulah engkau
memutuskan. Begitulah semua bicara (keputusan), benarlah sesuatu yang
memang benar-benar benar.
Dengarkanlah baik-baik ! bicaranya sebelah-menyebelah, (saksi kedua
belah pihak), jangan hanya sebelah saja, kau dengan bicaranya, bakalan
engkau makan, perbuatan yang engkau perbuat, orang yang diadili”,
itulah kata We Datu.
Kalau engkau tegas, berbicara dengan jujur, maka melimpah ruahlah
wisesamu, berikut pohon-pohonan yang lain, dan juga berkurang
penyakitnya. Itulah kusampaikan kepadamu, pabbicara yang jujur, jangan
sekali-sekali engkau mengambil untung ! juga jangan menerima sogok
(menerima suap), apabila engkau berbicara (mengadili), berbuat jujurlah
! jangan menerima marupe’ harta yang tidak jujur (tidak halal),
demikian pula yang datang malam (curian), akan merajalela penyakit,
tidak berhasil padi, berjatuhan buahnya, pohon-pohon yang dimakan.
Hilang pula semua ikan, semua isi sungai, apabila tidak baik, putusan
bicara (keadilan/hakim). Tidak baik akibatnya di kemudian hari,
merajalela penyakit, salah peraturan tuhanmu (tidak berhasil padi),
semuanya menjadi padang ilalang, wisesa Sangiangserri.
Apabila demikian, benar-benar bicara itu (keputusan yang adil), akan
berbicara dengan sendirinya padi-padimu itu, ramai berbunga, semua
tanaman-tanamanmu, akan mudah semuanya, semua yang memberi kehidupan,
semua tanam-tanaman, apabila engkau menjauhi semua pantangan,
pesan-pesannya, puang nenek mangkau’ku, batara yang melahirkanku, Opu
Batara Luwu .
Yakinilah engkau semua ! pada perkataan yang baik, keturunan I La
Patoto (Topalanroe), yang menetas di bambu betung (Tellang pulawenge),
sekianlah cerita-ceritanya, Datu Sangiangserri, berikut
sebut-sebutannya, Datu Meong Paloe (Rahman, N,1990)
Nilai dermawan dan pengasih itulah yang mendasari sikap dan perilaku
yang suka memberikan pertolongan atau jaminan sosial seperti yang ada
dalam cerita Meong Palo Karellae (MPK) : ”Mengantar orang yang
bepergian, menjemput orang yang datang, memberi makan orang yang lapar,
memberi minum orang yang haus, menyarungi orang yang telanjang,
menerima orang yang susah, menampung orang yang terdampar, menerima
orang yang dibenci, dan menerima semua orang yang diperlakukan
sewenang-wenang oleh sesama manusia” (M. Tang,2007). Sifat-sifat diatas
merupakan sifat yang terpuji bila ditinjau dari segi ilmu agama yang
mana mencintai sesama hamba Allah adalah lebih terpuji dan perilaku
tersebut menumbuh-kembangkan sifat kedermawanan (malabo) tidak kikir
(dena masekke) dengan perilaku ini membuat seseorang mempunyai
kelebihan tersendiri yang jarang diketemukan pada orang kebanyakan
karena dengan keikhlasan membuat seseorang merasa tenang dan tawaddu
(rendah diri) kepada Allah. Dulu pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan
masih ada orang-orang yang mempunyai perilaku seperti ini, namun
setelah masa orde reformasi perilaku seperti ini sudah jarang
ditemukan.
Mengenai pentingnya menjaga padi sebagai sumber bantuan, berulangkali
ditekankan perlunya menjaga padi dari serangan hama : ulat, nango,
burung pipit, tikus dan ular. Sesudah terjaga ari serangan hama,
ditekankan lagi perlunya memperlakukan padi secara baik (pasca panen),
yaitu jangan sampai terhambur tanpa dipungut, jangan dibiarkan dimakan
ayam dan tikus. Sesudah jadi nasi diingatkan lagi jangan sampai
dibiarkan jatuh berhamburan tanpa dipungut. Biar satu biji nasi yang
jatuh, juga harus dipungut.
Demikianlah artikel kali ini yang sempat Jendela Seni bagikan,semoga dapat bermanfaat,dan menambah wawasan keilmuan teman-teman khususnya mengenai salah satu episode dari epos La Galigo yaitu meong palo karellae.Dan jangan lupa di share!!!
- Home
- corak budaya Meong Palo Karellae Salah Satu Episode Dari Epos La Galigo
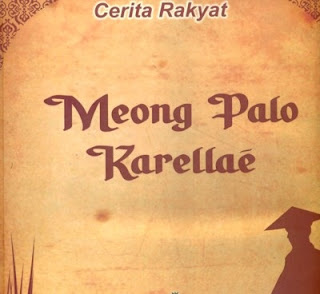





No comments:
Post a Comment